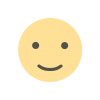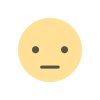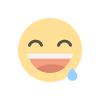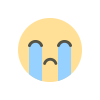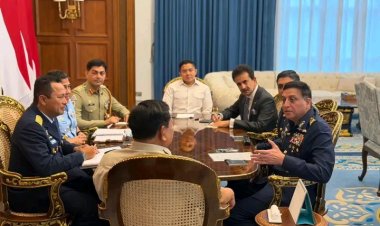Mencari Pemimpin Berkualitas di Tengah Wacana Pilkada DPRD

Yokyakarta, BBI.CO.ID-Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka di tengah kegelisahan publik terhadap mahalnya ongkos demokrasi. Pilkada langsung yang sejak awal dimaksudkan memperkuat kedaulatan rakyat justru kerap berubah menjadi ajang investasi politik.
Demikian disampaikan Drs.R Widi Handoko Ketua Papera DI Yogyakarta. Menurutnya, biaya kampanye yang membengkak, politik uang, hingga praktik serangan fajar telah menjerumuskan demokrasi ke dalam transaksi jangka pendek yang merusak akal sehat publik." tandasnya.
Mengembalikan modal
Dalam situasi ini, pilkada tidak lagi menjadi arena adu gagasan dan kapasitas kepemimpinan, melainkan kompetisi modal. Akibatnya bisa ditebak, Kepala Daerah terpilih terdorong “mengembalikan modal” melalui korupsi, jual beli kebijakan, dan penyalahgunaan kewenangan. Korupsi bukan anomali, melainkan konsekuensi logis dari sistem politik berbiaya tinggi.
Sebagian pihak lalu menawarkan pilkada melalui DPRD sebagai solusi. Secara teknis, model ini memang lebih hemat biaya dan menutup ruang transaksi langsung dengan pemilih. Ia juga dapat dibaca selaras dengan semangat demokrasi perwakilan dan musyawarah mufakat sebagaimana termaktub dalam sila keempat Pancasila - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Namun persoalan demokrasi Indonesia tidak sesederhana memilih mekanisme langsung atau tidak langsung. Pilkada lewat DPRD menyimpan risiko besar jika dilakukan dalam kondisi sistem yang rusak. Ia berpotensi memindahkan praktik transaksional dari bilik suara ke ruang rapat, dari politik uang terbuka ke lobi tertutup yang lebih senyap. Uangnya mungkin lebih rapi, tetapi problemnya tetap sama.
"Di sinilah letak persoalan mendasar yaitu krisis representasi. Lembaga perwakilan—DPR dan DPRD—semakin jauh dari fungsi idealnya sebagai penyambung kehendak rakyat. Banyak wakil rakyat lebih sibuk mengamankan kepentingan partai, sponsor politik, atau jaringan pribadi.
Fenomena ini mengafirmasi apa yang oleh Robert Michels disebut sebagai iron law of oligarchy - organisasi politik cenderung dikuasai oleh segelintir elite." papar alumni Departemen Hubungan Internasional UGM.
Partai politik yang seharusnya menjadi sekolah demokrasi justru terjebak sebagai mesin elektoral. Kaderisasi lemah, rekrutmen tidak transparan, dan tiket pencalonan ditentukan oleh kemampuan finansial, bukan integritas dan kapasitas. Samuel Huntington pernah mengingatkan, demokrasi tanpa institusionalisasi politik yang kuat hanya akan melahirkan instabilitas dan pembajakan kekuasaan oleh modal.
Karena itu, perdebatan pilkada sejatinya harus digeser. Bukan soal mekanisme pemilihan, melainkan bagaimana melahirkan pemimpin yang ideal dan kompeten.
Pemimpin berkualitas bukan sekadar pemenang kontestasi, tetapi sosok yang berintegritas, amanah, memiliki visi jelas, mampu berkomunikasi efektif, cerdas secara emosional, berempati, akuntabel, dan berani mengambil keputusan dengan pertimbangan etis. Ia harus menjadi teladan, mampu memotivasi dan mengembangkan tim, serta bertanggung jawabi atas dampak kebijakannya bagi publik.
Karena itu pula, negara perlu menetapkan standar ketat melalui peraturan perundang-undangan. Rekam jejak harus bersih, tidak pernah terlibat korupsi, kejahatan kesusilaan, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat. Setiap warga negara berhak mencalonkan diri, tetapi melalui mekanisme yang menjamin seleksi berbasis merit, bukan uang.
Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap partai politik dan lembaga perwakilan, pilkada—langsung maupun tidak langsung—hanya akan menjadi kosmetik demokrasi. Reformasi kelembagaan adalah prasyarat mutlak. Begitupun audit pendanaan partai, pembatasan biaya politik, kaderisasi berbasis kapasitas, dan pengawasan independen yang sungguh-sungguh.
Lebih dari itu, demokrasi tidak akan sehat jika rakyat terus diposisikan sebagai objek. Pendidikan politik warga menjadi kunci jangka panjang agar pilihan politik didasarkan pada rekam jejak, gagasan, dan integritas, bukan amplop sesaat. Peran negara, media, kampus, dan masyarakat sipil menjadi krusial dalam membangun literasi politik yang berkelanjutan.
Demokrasi bukan sekadar prosedur lima tahunan, melainkan etos keadilan, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Menurut dia, Selama sistem politik tetap mahal dan permisif terhadap oligarki, yang lahir bukan pemimpin negarawan, melainkan pemenang berbiaya tinggi.
Fokus utama kita seharusnya bukan pada cara memilih, tetapi siapa yang dipilih dan dengan standar apa ia layak memimpin.
"Tanpa itu, demokrasi hanya akan terus melahirkan kekuasaan yang sah secara prosedural, tetapi miskin secara moral dan substantif." pungkasnya.(bur)