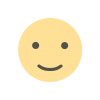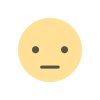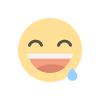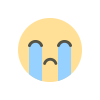Orkestrasi Pilkada Langsung atau Tidak Langsung: Elite Partai Politik dan Oligarki Menjelma Menjadi Monster

Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si (Akademisi, Analis Politik Lokal dan Ekonomi Politik Kebijakan Publik Kalimantan Selatan)
Wacana penghapusan pilkada langsung dan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah isu baru. Ia selalu muncul di saat-saat genting, ketika demokrasi dianggap mahal, melelahkan, dan sulit dikendalikan. Namun di balik alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik, tersimpan kepentingan yang jauh lebih berbahaya: hasrat elite partai dan oligarki untuk mengendalikan kekuasaan tanpa gangguan rakyat
Pilkada langsung sejatinya lahir dari semangat reformasi. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap sentralisasi kekuasaan dan kooptasi elite. Rakyat diberi hak menentukan pemimpinnya sendiri, sekaligus ruang untuk menghukum kekuasaan yang gagal. Ketika wacana pilkada tidak langsung kembali didorong, yang dipertaruhkan bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan substansi kedaulatan rakyat itu sendiri.
Elite partai politik kerap tampil sebagai aktor utama dalam orkestrasi ini. Dengan dalih memperkuat sistem presidensial dan menekan biaya politik, mereka menutup mata terhadap fakta bahwa biaya politik justru membengkak akibat praktik mahar politik, transaksi kekuasaan, dan politik balas jasa. Pilkada langsung sering dijadikan kambing hitam, padahal penyakit sesungguhnya berada di tubuh partai politik itu sendiri.
Di titik inilah oligarki menemukan momentumnya. Ketika kepala daerah dipilih oleh segelintir elite di parlemen daerah, ruang tawar-menawar menjadi lebih sempit dan mudah dikendalikan. Modal besar tak lagi perlu menyentuh rakyat banyak, cukup menyasar aktor-aktor kunci di ruang tertutup. Demokrasi pun berubah menjadi komoditas eksklusif, hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan modal dan jaringan kekuasaan.
Yang lebih mengkhawatirkan, proses ini berlangsung secara sistematis dan terencana.
Wacana dibangun, opini publik diarahkan, dan kegagalan demokrasi dibesar-besarkan tanpa evaluasi jujur terhadap akar masalahnya. Rakyat digiring untuk percaya bahwa mereka adalah sumber kekacauan, sementara elite tampil seolah penyelamat yang menawarkan solusi instan.
Padahal, pilkada langsung bukan tanpa manfaat. Ia telah melahirkan banyak pemimpin daerah yang tumbuh dari akar rumput, bukan dari rahim oligarki. Meski tak sedikit pula yang gagal, mekanisme demokrasi menyediakan ruang koreksi melalui pemilu berikutnya. Hak memilih dan dipilih adalah instrumen pembelajaran politik yang tidak bisa digantikan oleh kesepakatan elite.
Menghapus pilkada langsung tanpa membenahi partai politik sama saja memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang gelap. Ketika partai politik gagal berfungsi sebagai institusi kaderisasi dan pendidikan politik, lalu diberikan kekuasaan penuh memilih kepala daerah, maka yang lahir bukan efisiensi, melainkan monster kekuasaan yang rakus dan tak tersentuh kontrol publik.
Lebih jauh, narasi efisiensi anggaran yang kerap dijadikan alasan utama penghapusan pilkada langsung sesungguhnya menyederhanakan persoalan secara menyesatkan. Biaya besar dalam pilkada bukanlah akibat dari partisipasi rakyat, melainkan buah dari sistem politik yang permisif terhadap transaksi kekuasaan. Tanpa reformasi pendanaan partai, transparansi kampanye, dan penegakan hukum yang tegas, perubahan mekanisme pemilihan hanya akan mengubah jalur korupsi, bukan menghilangkannya.
Selain itu, pilkada tidak langsung berpotensi mematikan kontrol sosial di tingkat lokal. Kepala daerah yang lahir dari kompromi elite cenderung lebih loyal kepada partai dan penyokong modal ketimbang kepada rakyat. Akibatnya, kebijakan publik berisiko menjauh dari kebutuhan warga, sementara kritik masyarakat dipandang sebagai gangguan, bukan koreksi. Dalam situasi ini, ruang partisipasi publik menyempit, dan demokrasi lokal berubah menjadi sekadar prosedur administratif tanpa roh.
Jika orkestrasi ini dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya sistem pemilihan, tetapi kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri. Rakyat yang merasa suaranya tak lagi berarti akan menarik diri dari proses politik, membuka jalan bagi apatisme massal dan radikalisme kekecewaan. Inilah titik paling berbahaya: ketika elite dan oligarki mengira telah mengamankan kekuasaan, padahal sesungguhnya sedang menanam bom waktu bagi stabilitas politik dan masa depan demokrasi bangsa.
Pilkada langsung atau tidak langsung sejatinya bukan sekadar pilihan sistem, melainkan cermin keberpihakan. Apakah negara berdiri di sisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan, atau justru tunduk pada elite dan oligarki yang menjelma menjadi monster demokrasi. Jika pilihan jatuh pada yang kedua, maka kita sedang menyaksikan kemunduran sejarah yang disengaja dan rakyatlah yang akan menanggung akibatnya.