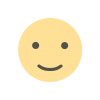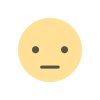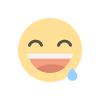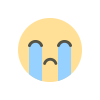Doa Iftitah: Penegasan Status Kita di Hadapan Allah

Ashar Tamanggong
(Pembimbing Haji Patria Wisata)
Setelah takbiratul ihram, ada satu momen yang sering kita lewati dengan kecepatan tinggi. Mulut bergerak, hati tertinggal. Namanya doa iftitah. Padahal inilah kalimat pembuka audiensi kita dengan Allah. Kalau sholat itu pertemuan resmi, doa iftitah adalah pernyataan identitas: siapa kita, dan siapa Dia.
Masalahnya, banyak dari kita membaca doa iftitah seperti membaca syarat dan ketentuan aplikasi—panjang, formal, dan jarang direnungkan. Yang penting selesai. Padahal isinya bukan basa-basi. Isinya sangat serius: penegasan status kehambaan.
Coba perhatikan salah satu redaksinya:
“Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh…”
“Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi.”
Kalimat ini sebenarnya pengakuan yang berat. Kita sedang berkata, “Ya Allah, sekarang aku benar-benar menghadap kepada-Mu.” Bukan setengah-setengah. Bukan sambil melirik dunia. Bukan sambil memikirkan yang lain.
Tapi jujur saja, sering kali wajah kita menghadap kiblat, hati menghadap ke mana-mana.
Isra’ Mi’raj mengajarkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ benar-benar dihadapkan kepada Allah. Tidak ada pengalihan. Tidak ada gangguan. Tidak ada kepentingan lain. Dan sholat, sebagai hadiah dari peristiwa itu, mengajak kita meniru sikap tersebut—meski dalam versi manusia biasa.
Doa iftitah juga mengandung pengakuan identitas:
“Wa maa ana minal musyrikin.”
“Aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan.”
Ini bukan hanya soal patung atau berhala. Di zaman sekarang, syirik sering berbentuk halus: terlalu menggantungkan diri pada jabatan, relasi, angka saldo, atau penilaian manusia. Kita mungkin tidak sujud pada patung, tapi sering takut berlebihan pada makhluk.
Maka doa iftitah itu seperti tamparan lembut: “Hei, sebelum lanjut sholat, luruskan dulu orientasi hidupmu.”
Lalu ada bagian yang lebih menohok:
“Inna shalaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillaahi rabbil ‘aalamiin.”
“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah.”
Ini bukan kalimat kecil. Ini deklarasi total. Sayangnya, sering kita ucapkan dengan mulut yang fasih, tapi hidup kita masih penuh kompromi. Sholat untuk Allah, tapi hidup untuk gengsi. Ibadah untuk Allah, tapi keputusan hidup untuk pujian manusia.
Doa iftitah seakan bertanya pelan:
“Benarkah hidupmu hanya untuk Allah, atau sekadar sholatmu saja?”
Isra’ Mi’raj adalah perjalanan Nabi ﷺ sebagai hamba, bukan sebagai raja, bukan sebagai tokoh besar, tapi sebagai ‘abd—hamba. Bahkan Al-Qur’an menyebut: Subhaanal ladzi asraa bi ‘abdihi… Yang diisra’kan itu hamba-Nya. Dan doa iftitah mengembalikan kita ke titik itu: kita ini siapa.
Kita bukan pemilik hidup. Kita bukan pusat semesta. Kita hanya hamba yang diberi kesempatan berdiri sebentar di hadapan Allah. Maka wajar kalau doa iftitah isinya pujian, pengakuan, dan penyerahan diri.
Tapi sering kali kita kebalik. Baru berdiri sholat, sudah sibuk mengatur Allah lewat doa-doa panjang di sujud nanti. Padahal di awal saja, kita belum benar-benar menyerahkan diri.
Ada juga bagian doa iftitah yang mengatakan:
“Zhalamtu nafsi dzulman katsiraa.”
“Aku telah menzalimi diriku sendiri.”
Ini pengakuan jujur. Tanpa pencitraan. Tanpa topeng. Di hadapan Allah, kita tidak perlu terlihat sempurna. Justru kejujuran itulah yang membuka pintu rahmat.
Sayangnya, di luar sholat kita sering gengsi mengakui salah. Tapi di dalam sholat, Allah mengajari adab: rendahkan diri dulu, baru minta.
Doa iftitah itu seperti mengisi biodata spiritual: nama kita hamba, status kita lemah, kebutuhan kita rahmat, dan tujuan kita ridha Allah. Kalau biodata ini tidak jelas, jangan heran kalau sholat terasa hambar.
Serial Isra’ Mi’raj ini terus mengingatkan: setiap gerakan sholat adalah pelajaran hidup. Doa iftitah mengajarkan bahwa sebelum kita bicara panjang lebar kepada Allah, tegaskan dulu posisi kita.
Bukan sebagai bos yang menuntut. Bukan sebagai pelanggan yang komplain. Tapi sebagai hamba yang sadar diri.
Maka mulai saat ini, ketika membaca doa iftitah, jangan dikejar cepat. Pelankan. Resapi. Biarkan ia menertibkan ego. Karena kalau status kita sudah jelas—Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba—maka ayat-ayat berikutnya akan terasa lebih hidup.
Sebab sholat yang benar tidak dimulai dari bacaan Al-Fatihah, tapi dari kesadaran mendalam dalam doa iftitah:
aku ini hamba, dan Engkau adalah Allah.
Wallahu A'lam