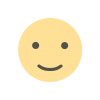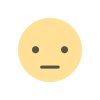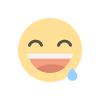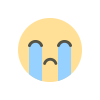Al-Fatihah: Sholat itu Dialog bukan Monolog

Ashar Tamanggong
(Pembimbing Haji Patria Wisata)
Banyak orang mengira sholat itu monolog. Kita bicara, Allah mendengar. Selesai. Padahal dalam sholat, khususnya saat membaca Surat Al-Fatihah, yang terjadi bukan monolog, tapi dialog. Dua arah. Kita membaca, Allah menjawab. Bedanya, jawaban Allah tidak terdengar di telinga, tapi dirasakan oleh hati yang mau hadir.
Rasulullah ﷺ menjelaskan dalam hadits qudsi bahwa Allah berfirman, “Aku membagi sholat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian…” Lalu setiap ayat Al-Fatihah dibalas oleh Allah. Artinya, saat Al-Fatihah dibaca, sebenarnya kita sedang bercakap-cakap dengan Sang Khaliq.
Masalahnya, banyak dari kita membaca Al-Fatihah seperti membaca pengumuman—cepat, datar, tanpa rasa. Kita bicara, tapi tidak sadar sedang diajak bicara balik. Padahal kalau sadar ini dialog, mungkin bacaan kita akan lebih pelan, lebih sopan, dan lebih jujur.
Isra’ Mi’raj adalah momen dialog paling agung antara Nabi Muhammad ﷺ dan Allah. Tanpa perantara. Tanpa hijab. Dan sholat—hadiah dari peristiwa itu—adalah cara Allah membuka ruang dialog itu untuk kita semua. Gratis. Lima kali sehari. Tinggal mau atau tidak.
Ayat pertama kita ucapkan:
Alhamdulillahi Rabbil ‘aalamiin.
Dan Allah menjawab, “Hamba-Ku telah memuji-Ku.”
Bayangkan, baru satu ayat, Allah sudah merespons. Tapi kita sering membaca tanpa rasa syukur yang nyata. Lidah memuji, hati masih mengeluh. Kita bilang “segala puji bagi Allah”, tapi setelah salam, sedikit-sedikit protes hidup.
Ayat berikutnya:
Ar-Rahmaanir-Rahiim.
Allah menjawab, “Hamba-Ku telah menyanjung-Ku.”
Di sini kita mengakui kasih sayang Allah. Tapi sering kali, kita lebih cepat mengingat luka daripada nikmat. Lebih hafal kecewa daripada karunia. Al-Fatihah mengajari adab dialog: kenali dulu sifat Tuhanmu sebelum mengadu panjang lebar.
Lalu kita baca:
Maaliki yaumid diin.
Dan Allah berkata, “Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku.”
Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan cuma hari ini. Ada hari pembalasan. Ada tanggung jawab. Tapi anehnya, kita sering ingin rahmat Allah, tapi lupa bahwa Dia juga Maha Adil.
Masuk ke inti dialog:
Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin.
Allah menjawab, “Ini antara Aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.”
Di sini kita berjanji setia. Menyembah hanya kepada Allah, dan meminta pertolongan hanya kepada-Nya. Tapi sering janji ini kita ucapkan sambil lalu. Setelah sholat, pertolongan pertama yang dicari justru manusia, koneksi, dan cara-cara dunia. Allah dijadikan opsi terakhir.
Padahal Al-Fatihah sedang mengajarkan dialog yang jujur: jangan berjanji kalau tidak siap menepati.
Lalu kita mengajukan permohonan:
Ihdinash shiraathal mustaqiim.
Dan Allah berkata, “Ini untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku akan mendapatkannya.”
Perhatikan, yang dijamin Allah adalah petunjuk, bukan langsung hasil. Jalan, bukan tujuan instan. Karena Allah tahu, manusia sering salah arah tapi merasa benar. Ok
Dan di ayat terakhir, kita menutup dialog dengan kesadaran sejarah: ada jalan orang-orang yang diberi nikmat, ada jalan yang dimurkai, ada jalan yang sesat. Kita diminta memilih, bukan sekadar mengeluh.
Sayangnya, dialog seindah ini sering kita rusak sendiri. Kita bicara cepat, tidak menunggu “jawaban”. Kita hadir secara fisik, tapi batin absen. Kita ingin didengar, tapi lupa mendengar.
MV cari AQ
Padahal dialog butuh kehadiran. Kalau sholat hanya formalitas, Al-Fatihah kehilangan ruhnya. Ia tinggal bacaan wajib, bukan percakapan hidup.
Isra’ Mi’raj mengajarkan bahwa Allah dekat, bukan jauh. Dan Al-Fatihah membuktikannya. Lima waktu sehari, Allah memberi ruang bagi hamba-Nya untuk bicara—bahkan menanggapi.
Maka lain kali membaca Al-Fatihah, jangan terburu-buru. Bayangkan Anda sedang berdialog. Ucapkan, lalu diam sejenak di hati. Rasakan jawabannya. Tidak selalu berupa kata, tapi berupa ketenangan.
Karena ketika Al-Fatihah dibaca dengan sadar, sholat tidak lagi terasa sebagai kewajiban berat, tapi sebagai pertemuan intim antara hamba yang lemah dan Tuhan yang Maha Mendengar.
Dan di situlah Isra’ Mi’raj terasa hidup—bukan di langit yang jauh, tapi di hati yang sedang berdialog dengan Allah.
Wallahu A'lam