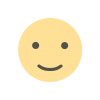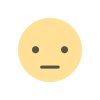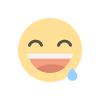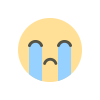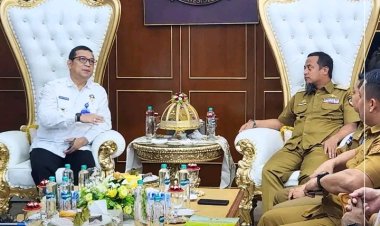Rukuk: Sebuah Pengakuan akan Keagungan Alla

Ashar Tamanggong
Pembimbing Haji Patria Wisata
*Setelah berdiri tegak, membaca Al-Fatihah dengan penuh dialog, sholat mengajak kita melakukan satu gerakan yang sederhana tapi sarat makna: rukuk. Punggung dibungkukkan, kepala direndahkan, pandangan ke tempat sujud. Seolah sholat ingin berkata, “Sekarang, bukan waktunya bicara panjang. Sekarang waktunya mengakui kebesaran Allah.”
Bacaan rukuk sangat singkat:
Subhaana rabbiyal ‘azhiim.
“Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung.”
Tapi jangan tertipu oleh pendeknya kalimat ini. Karena di sinilah ego manusia mulai diuji.
Selama ini kita hidup dengan posisi “tegak”. Tegak jabatan. Tegak gengsi. Tegak merasa paling benar. Bahkan saat sholat pun, masih banyak yang tegak egonya. Maka rukuk hadir sebagai koreksi: yang pantas tegak hanya Allah, manusia pantas menunduk.
Isra’ Mi’raj memperlihatkan bagaimana seluruh langit tunduk kepada Allah. Para malaikat, para nabi, seluruh makhluk—semuanya berada dalam keteraturan yang rapi, penuh kepatuhan. Dan rukuk adalah latihan kecil kita untuk masuk ke dalam irama kosmik itu.
Lucunya, ada orang yang badannya sudah rukuk, tapi hatinya masih berdiri. Badan menunduk, tapi pikiran masih sombong. Mulut membaca tasbih, tapi batin masih sibuk menilai orang lain. Ini rukuk versi fisik, belum sampai versi spiritual.
Padahal rukuk itu simbol pengakuan. Pengakuan bahwa ada yang lebih besar dari kita. Pengakuan bahwa tidak semua bisa kita kendalikan. Pengakuan bahwa sehebat apa pun manusia, tetap ada batas.
Coba perhatikan posisi rukuk. Kepala sejajar dengan punggung. Tidak lebih tinggi. Tidak lebih rendah. Ini pelajaran halus tentang keseimbangan. Kita diminta rendah hati, tapi tidak minder. Tunduk, tapi bukan hina. Karena rukuk bukan untuk merendahkan diri di hadapan manusia, tapi untuk meninggikan Allah.
Masalah hidup sering terasa berat karena kita terlalu lama “tegak”. Terlalu keras mempertahankan pendapat. Terlalu kaku mempertahankan ego. Padahal hidup akan lebih ringan kalau sesekali kita belajar menunduk.
Rukuk juga mengajarkan jeda. Dari dialog panjang Al-Fatihah, kita berhenti sejenak. Menunduk. Bertasbih. Dalam dunia yang ribut oleh suara, rukuk adalah momen hening. Mengakui kebesaran Allah tanpa banyak kata.
Dan bacaan Subhaana rabbiyal ‘azhiim itu bukan hanya pujian, tapi pembersihan. Kita mensucikan Allah dari semua gambaran kecil versi kita. Karena sering kali kita mengecilkan Allah sesuai kepentingan kita. Kita ingin Allah cepat menolong, tapi lupa bahwa Dia Maha Bijaksana.
Isra’ Mi’raj mengajarkan bahwa keagungan Allah tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Dan rukuk melatih kita menerima itu. Tidak semua harus dimengerti. Tidak semua harus dijelaskan. Ada saatnya cukup mengakui: Allah Maha Agung, titik.
Sayangnya, banyak orang rajin rukuk tapi masih sulit menerima kenyataan. Ketika doa belum dikabulkan, kita protes. Ketika hidup tidak sesuai rencana, kita kecewa. Padahal rukuk setiap hari seharusnya melatih kita berkata dalam hati: “Aku tidak selalu tahu yang terbaik, tapi Allah Maha Tahu.”
Rukuk juga menampar kesombongan sosial. Di shaf sholat, semua rukuk bersama. Yang kaya, yang miskin. Yang pejabat, yang rakyat. Semua punggung sejajar. Semua kepala sama rendah. Tidak ada VIP di rukuk. Ini pelajaran peradaban yang luar biasa.
Kalau nilai rukuk dibawa ke luar masjid, mungkin kita tidak akan mudah merendahkan orang lain. Karena kita ingat, di hadapan Allah, kita semua pernah sama-sama menunduk.
Serial Isra’ Mi’raj ini mengajak kita melihat bahwa sholat bukan sekadar ritual, tapi perjalanan batin. Dan rukuk adalah salah satu stasiunnya: stasiun pengakuan.
Maka lain kali rukuk, jangan buru-buru. Rasakan punggung menunduk. Biarkan ego ikut turun. Bisikkan tasbih bukan hanya dengan lidah, tapi dengan kesadaran:
“Ya Allah, Engkau Maha Agung. Aku ini kecil.”
Karena siapa yang benar-benar mengakui keagungan Allah dalam rukuk, biasanya akan lebih lapang hatinya dalam menghadapi hidup.
Dan di situlah rukuk menemukan maknanya—bukan sekadar gerakan, tapi pengakuan tulus akan keagungan Allah.
Wallahu A'lam