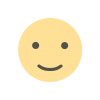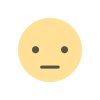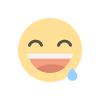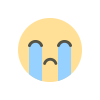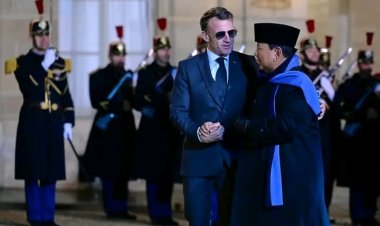Ibadah Haji: Perjalanan Spiritual Panjang

Ashar Tamanggong
Ketua Baznas Makassar
Ibadah haji sering kita bayangkan sebagai perjalanan jauh ke Tanah Suci. Naik pesawat belasan jam, transit sana-sini, lalu tiba di Makkah. Tapi sesungguhnya, haji bukan sekadar perjalanan geografis. Haji adalah perjalanan spiritual yang sangat panjang—bahkan lebih panjang dari antrean keberangkatan haji itu sendiri. Kalau antrean haji di Indonesia bisa 20–30 tahun, perjalanan spiritualnya bisa seumur hidup, kalau mau jujur pada diri sendiri.
Perjalanan haji itu dimulai jauh sebelum koper dikunci. Bahkan sebelum paspor dipegang. Ia dimulai dari niat. Dari pertanyaan sederhana tapi sering dihindari: “Saya ke Baitullah ini mau apa?” Mau ibadah, atau mau status? Mau mabrur, atau mau gelar “Pak Haji” biar dipanggil duluan di acara keluarga? Jangan tersinggung dulu, ini sekadar muhasabah. Karena niat itu seperti SIM, kalau tidak jelas, perjalanan bisa tersesat meski jalannya lurus.
Sejak mendaftar haji, sebenarnya Allah sudah mulai mendidik kita. Menunggu bertahun-tahun adalah latihan sabar tingkat tinggi. Di situlah kita belajar bahwa haji bukan untuk orang yang tergesa-gesa. Yang tidak sabar antre di loket saja, biasanya mudah emosi di Mina. Yang di rumah masih suka menyerobot antrian, di Tanah Suci sering lupa kalau thawaf itu muter, bukan nyalip.
Lalu tibalah kita di Makkah. Di sana, pelajaran pertama dimulai dari pakaian ihram. Semua dilepas: jabatan, pangkat, status sosial, bahkan merek pakaian. Yang biasanya pakai baju mahal, sekarang pakai kain dua helai. Yang biasa dihormati, sekarang harus sabar diinjak sandalnya. Ihram itu pesan sunyi dari Allah: “Di hadapan-Ku, kamu semua sama.” Kalau di dunia kita sering berlomba kelihatan hebat, di ihram kita dilatih terlihat sederhana.
Thawaf mengajari kita tentang konsistensi. Mengelilingi Ka’bah tujuh kali, arah yang sama, tujuan yang sama. Seperti hidup, seharusnya berputar di poros tauhid. Jangan hidup muter-muter tapi menjauh dari Allah. Banyak orang capek bukan karena banyak aktivitas, tapi karena hidupnya tidak jelas arah. Thawaf mengajarkan: capek itu boleh, asal arahnya benar.
Sa’i antara Shafa dan Marwah adalah pelajaran ikhtiar tanpa drama. Hajar berlari, bukan karena panik, tapi karena yakin Allah melihat usahanya. Air Zamzam keluar bukan di Shafa, bukan di Marwah, tapi di kaki Ismail—di titik yang tidak disangka. Ini pelajaran hidup: sering kali rezeki datang bukan di tempat kita merasa paling pintar, tapi di saat kita paling tawakkal.
Wukuf di Arafah adalah momen paling sunyi, tapi paling ramai makna. Semua jamaah berhenti. Tidak thawaf, tidak sa’i. Diam. Berdoa. Menangis. Mengingat dosa-dosa lama yang dulu dianggap “biasa”. Di Arafah kita sadar, ternyata yang paling kita butuhkan bukan wifi, tapi ampunan. Bukan sinyal, tapi rahmat Allah. Kalau di dunia kita sibuk bicara, di Arafah kita diajari mendengar suara hati sendiri.
Lontar jumrah sering disalahpahami. Yang dilempar itu bukan setan fisik, tapi sifat setan dalam diri: sombong, dengki, malas, suka menunda taubat. Sayangnya, banyak yang semangat melempar kerikil, tapi lupa melempar egonya. Kerikilnya habis, emosinya masih utuh. Pulang dari haji, masih mudah marah, masih ringan ghibah. Jangan-jangan yang kena lontar cuma temboknya, bukan penyakit hatinya.
Namun, haji tidak selesai di Tanah Suci. Justru ujian terberatnya dimulai setelah pulang. Di rumah. Di kantor. Di jalan raya. Haji mabrur itu kelihatan dari perubahan: shalat lebih dijaga, lisan lebih santun, emosi lebih terkendali. Kalau sebelum haji mudah marah, setelah haji harus lebih sulit marah. Kalau sebelum haji susah memaafkan, setelah haji harus lebih ringan memaafkan.
Haji adalah perjalanan spiritual yang sangat panjang. Ia tidak diukur dengan jarak, tapi dengan perubahan akhlak. Tidak ditandai dengan foto di depan Ka’bah, tapi dengan sikap di tengah masyarakat. Sebab sejatinya, haji bukan tentang sejauh apa kita melangkah ke Makkah, tapi sejauh apa hati kita melangkah menuju Allah.