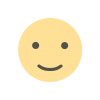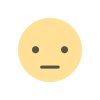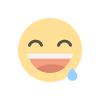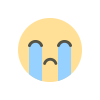Ketika Negara Berubah Menjadi Rumah Pembegalan bagi Rakyat

Dr Muhammad Uhaib As'ad M.Si
Negeri ini pelan tapi pasti bermetamorfosis menjadi sebuah rumah pembegalan bagi rakyatnya sendiri. Pembegalan yang dimaksud bukanlah kejahatan jalanan dengan senjata tajam, melainkan praktik perampasan hak yang berlangsung terang-benderang, sistematis, dan kerap dilegalkan melalui kebijakan. Rakyat tidak lagi dirampas oleh perampok di lorong gelap, tetapi oleh mekanisme negara yang semestinya hadir sebagai pelindung.
Pembegalan itu dimulai dari hak paling mendasar: hidup layak, rasa aman, dan kepastian masa depan. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara pendapatan rakyat tidak bergerak sepadan. Negara terlihat hadir, tetapi sering kali hanya sebagai penonton—atau lebih buruk, sebagai wasit yang condong pada kepentingan pemodal. Bu
Di sektor ekonomi, logika pasar yang keras diberlakukan tanpa bantalan perlindungan sosial yang memadai. Subsidi dipangkas atas nama efisiensi, sementara pajak dan retribusi kian kreatif mencari celah. Ketika rakyat mengeluh, jawaban yang muncul nyaris seragam: keterbatasan anggaran, tekanan global, atau warisan masalah masa lalu.
Ironi makin kentara ketika rakyat diminta berhemat, sementara sebagian elite mempertontonkan kemewahan. Proyek mercusuar berdiri megah, perjalanan dinas terus berjalan, dan seremoni negara tak pernah sepi. Semua tampak normal di permukaan, namun di bawahnya tersimpan jeritan yang kerap diabaikan.
Dalam pelayanan publik, pembegalan hadir lewat birokrasi yang berbelit. Mengurus hak sendiri menjadi perjalanan panjang penuh administrasi, pungutan tak resmi, dan sikap aparat yang kerap arogan. Negara perlahan bergeser dari pelayan menjadi penguasa yang harus dihadapi dengan rasa takut.
Penegakan hukum pun mengalami erosi makna. Keadilan terasa mahal dan sulit dijangkau. Mereka yang kuat modal dan kuasa kerap menemukan jalan keluar, sementara rakyat kecil harus menelan kenyataan pahit. Hukum tidak lagi sepenuhnya menjadi alat keadilan, melainkan alat penertiban bagi yang lemah.
Di sektor sumber daya alam, pembegalan berlangsung masif. Tanah, hutan, dan sungai berpindah tangan atas nama investasi. Masyarakat lokal tersingkir dari ruang hidupnya sendiri dan dipaksa menanggung dampak lingkungan tanpa kompensasi yang adil.
Negara sering berdalih bahwa pembangunan menuntut pengorbanan. Namun pertanyaan mendasarnya sederhana: mengapa pengorbanan itu hampir selalu dibebankan kepada rakyat kecil, sementara keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak?
Di bidang pendidikan dan kesehatan, rakyat kembali menjadi korban. Akses kian mahal, kualitas tak merata, dan tanggung jawab negara perlahan digeser menjadi urusan individu. Siapa yang mampu bertahan, dia selamat; siapa yang tidak, dipaksa berjuang sendiri.
Ruang publik kemudian dipenuhi narasi pencitraan. Statistik dipoles, keberhasilan dibesarkan, kritik dicurigai. Negara tampak sibuk merawat citra, sementara luka sosial dibiarkan menganga.
Pembegalan paling terasa ketika suara rakyat makin kehilangan ruang. Aspirasi dianggap gangguan, kritik dicap kebencian, dan perbedaan pandangan dipersempit. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan rohnya.
Negeri ini seakan lupa bahwa kekuasaan bersumber dari rakyat. Amanat keadilan sosial yang tertulis dalam konstitusi terasa kian jauh dari praktik. Dalam keseharian, rakyat justru terus diminta mengalah.
Pembegalan juga berlangsung halus melalui bahasa kebijakan. Istilah seperti efisiensi, penyesuaian, dan rasionalisasi anggaran dipakai untuk menutupi kenyataan bahwa beban dipindahkan ke pundak rakyat. Bahasa dibuat dingin agar penderitaan terasa wajar.
Di tingkat daerah, pola serupa direproduksi. Pemerintah lokal sering kali menjadi perpanjangan kebijakan pusat tanpa keberanian membela warganya. Aspirasi berhenti di ruang dengar pendapat, lalu menguap di meja rapat tertutup.
Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini perlahan dinormalisasi. Rakyat diajari pasrah, menerima ketidakadilan sebagai takdir, bukan sebagai akibat dari keputusan politik. Di situlah kekalahan paling sunyi terjadi. Solidaritas sosial pun diuji. Rakyat dipertemukan dalam kompetisi sesama korban: siapa yang paling layak dibantu dan siapa yang harus menunggu. Negara absen, masyarakat dipaksa saling menghakimi.
Sejarah berulang kali mengingatkan, negara yang menjauh dari rakyatnya sedang menciptakan jarak berbahaya—bukan hanya jarak kebijakan, tetapi jarak emosional. Ketika empati hilang dari kekuasaan, legitimasi moral ikut terkikis.
Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar harus diajukan kembali: untuk siapa negeri ini dibangun? Jika jawabannya bukan rakyat, maka sekuat apa pun bangunan kekuasaan berdiri, fondasinya sesungguhnya rapuh.
Dan ketika fondasi itu runtuh, yang tersisa bukan sekadar krisis kepercayaan, melainkan ingatan kolektif tentang sebuah negeri yang pernah berjanji melindungi, namun perlahan berubah menjadi rumah pembegalan bagi rakyatnya sendiri.